TarunaKota.com, Jakarta – Memasuki era Anthropocene, pemerintah terus berupaya menyelamatkan ekosistem alam demi keberlangsungan hidup manusia. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah memperkuat komitmen dalam melindungi hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia. Langkah ini bertujuan untuk memastikan keberadaan serta budaya masyarakat hukum adat tetap terlindungi dari ancaman penggusuran dan eksploitasi sumber daya alam.
RUU Masyarakat Hukum Adat dalam Prolegnas 2025
Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Agustin Teras Narang, mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat terus digodok oleh pemerintah. RUU ini telah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Proses penyusunan RUU ini sebenarnya sudah dimulai sejak 2008, namun hingga kini masih menghadapi berbagai tantangan.
“Tugas ini berat karena RUU yang terkait dengan masyarakat hukum adat menghadapi banyak penolakan, baik secara internal maupun eksternal,” ujar Teras dalam Diskusi Publik yang diadakan oleh Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) pada Senin (17/3/2025).
Teras menjelaskan bahwa penolakan eksternal berasal dari negara-negara yang masih bergantung pada sumber daya alam Indonesia. Namun, sesuai dengan mandat UUD 1945, masyarakat hukum adat harus memiliki undang-undang yang mampu melindungi mereka beserta sumber daya alam di sekitarnya.
“Masyarakat hukum adat bukan hanya butuh pengakuan, tetapi juga perlindungan dan pemberdayaan,” tegasnya.
Prinsip Penting dalam Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
Direktur Program IOJI, Stephanie Juwana, menyoroti beberapa prinsip penting yang perlu diadopsi dalam hukum nasional demi menyelamatkan masyarakat hukum adat dan ekosistem alam. Selama ini, praktik-praktik yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat memiliki peran signifikan dalam mengurangi tekanan terhadap lingkungan atau planetary pressures.
Planetary pressures merujuk pada dampak aktivitas manusia terhadap sistem planet Bumi, seperti eksploitasi sumber daya alam, polusi, perubahan iklim, dan degradasi lingkungan. Stephanie menegaskan bahwa dalam hal pemulihan dan konservasi ekosistem, metode yang diterapkan oleh masyarakat hukum adat lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan pemerintah.
“Dalam memperbaiki dan menjaga ekosistem alam, praktik yang dilakukan masyarakat hukum adat lebih baik dibandingkan pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah. Mereka memiliki cara sendiri dalam memperbaiki lingkungan,” jelasnya.
Dasar Konstitusional Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
Di Indonesia, landasan konstitusional perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Pasal ini mengatur tentang pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Stephanie menambahkan bahwa jika pasal ini dipadukan dengan pasal-pasal lain yang berhubungan dengan arah pembangunan nasional, maka akan muncul gambaran yang lebih luas mengenai upaya Indonesia dalam meningkatkan peran masyarakat hukum adat. Dengan demikian, masyarakat hukum adat dapat turut serta dalam beberapa agenda strategis nasional yang tertuang dalam Asta Cita dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).
“Ada keselarasan nilai-nilai dan praktik yang dilakukan masyarakat hukum adat yang dapat mendukung agenda-agenda tersebut,” ujarnya.
Dia juga menyoroti nilai-nilai penting dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang diwariskan melalui praktik adat, seperti pengakuan batas ekologis dalam pemanfaatan sumber daya alam, pendekatan spiritual dalam menjaga keseimbangan ekologi, penerapan prinsip strong sustainability, serta menjamin keadilan ekologis bagi generasi sekarang dan mendatang.
Tantangan Regulasi terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat
Sayangnya, nilai-nilai adat tersebut kini menghadapi tantangan dari berbagai regulasi, termasuk UU Cipta Kerja dan aturan turunannya yang mengatur proyek strategis nasional (PSN). PSN justru menjadi ancaman terhadap hak-hak masyarakat hukum adat, terutama terkait dengan perubahan fungsi kawasan hutan lindung dan hutan konservasi. Selain itu, UU Minerba sering kali memicu konflik berkepanjangan antara industri pertambangan dengan masyarakat hukum adat.
“PSN ini justru menimbulkan ancaman pada hak-hak masyarakat hukum adat. Sehingga, perlu adanya penguatan dalam melindungi hak-hak mereka,” tegas Stephanie.
Rekomendasi Aksi untuk Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat
IOJI merekomendasikan lima langkah aksi bagi negara untuk meningkatkan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat, yaitu:
- Mengesahkan RUU Masyarakat Hukum Adat untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak mereka.
- Mencabut atau merevisi regulasi yang mengancam keberlanjutan masyarakat hukum adat, termasuk beberapa pasal dalam UU Cipta Kerja dan UU Minerba.
- Memperkuat kelembagaan pemerintah yang bertugas melindungi hak-hak masyarakat hukum adat.
- Menegaskan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat dalam amandemen UUD 1945.
- Membangun jaringan masyarakat hukum adat di tingkat regional, nasional, dan global guna memperkuat advokasi dan dukungan internasional.
Dengan implementasi rekomendasi ini, diharapkan hak-hak masyarakat hukum adat dapat semakin terlindungi, sehingga mereka dapat terus berkontribusi dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan lingkungan di Indonesia. (Amelia)
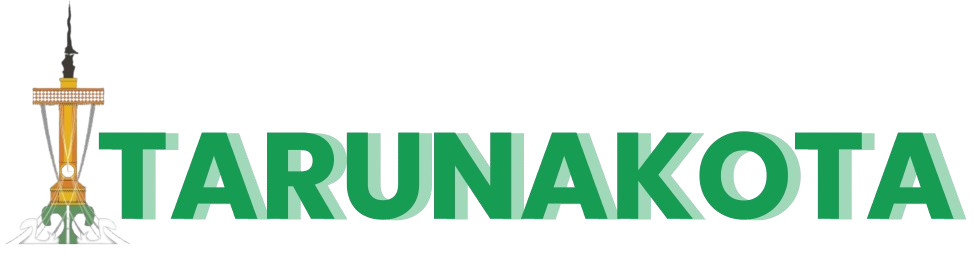




Tinggalkan Balasan